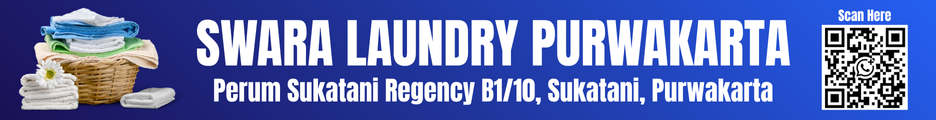Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, semakin aktif menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial. Banyak orang memilih untuk melakukan aksi boikot dan cancel culture sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap barang, orang, atau institusi yang mereka anggap melanggar etika atau identitas kolektif.
Namun, di balik rasa solidaritas tersebut, apakah itu hanya manifestasi kesadaran atau hanyalah akibat tekanan sosial digital?
Akar Budaya Boikot di Indonesia
Sebagaimana Jaafar dan Herna (2023) jelaskan, budaya boikot di Indonesia bukan hanya fenomena global. Ia berasal dari nilai agama dan politik identitas yang sangat memengaruhi dinamika sosial kita. Kampanye boikot terhadap merek global seperti merek-merek asal negeri Paman Sam tidak hanya berkaitan dengan keuntungan moneter. Gerakan ini berfokus pada masyarakat Muslim Indonesia yang merasa perlu menyuarakan posisi politik mereka dan menyatakan solidaritas.

Namun, ketika media sosial digunakan untuk menyebarkan opini, ada aturannya sendiri. Instagram dan Twitter meningkatkan masalah viral berdasarkan frekuensi interaksi daripada kualitas konten. Akibatnya, masyarakat sering terbawa oleh budaya cancel tanpa sempat memverifikasi apa yang mereka dengar. Menurut penelitian Lestari et al. (2024), tekanan sosial digital di Indonesia memengaruhi keputusan tentang siapa yang berhak “diboikot”.
Baca juga: https://naramakna.id/pergeseran-bahasa-dari-ungkapan-alam-ke-digital/
Batas antara Aktivisme dan Represi Sosial
Selain itu, menurut Stuart Hall (1997), budaya adalah medan kontestasi makna. Boikot dapat kita anggap sebagai upaya untuk melindungi nilai-nilai lokal dari pengaruh nilai-nilai internasional. Namun, cancel culture dapat berubah menjadi bentuk represi sosial ketika kita lakukan secara membabi buta. Orang yang berpendapat berbeda biasanya mereka anggap tidak bermoral atau bahkan pengkhianat.
Cancel culture tidak seharusnya hanya menjadi tindakan massa yang emosional. Bukan sekadar menekan tombol “unfollow” atau “boikot” berdasarkan tren, kita membutuhkan literasi digital dan keberanian untuk berbicara. Karena demokrasi membutuhkan ruang untuk persetujuan dan ketidaksepakatan, publik harus tetap kritis dan adil di tengah semangat aktivisme digital.
Kita harus menyadari bahwa, jika kita lakukan secara sadar dan kritis, boikot dan cancel culture dapat berfungsi sebagai kekuatan yang membebaskan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat tekanan yang mencegah kebebasan berekspresi. Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, keberagaman pandangan seharusnya tidak selalu kita sikapi dengan kekerasan. Sebaliknya, ia seharusnya kita jembatani dengan diskusi dan upaya untuk mencapai kesepakatan.